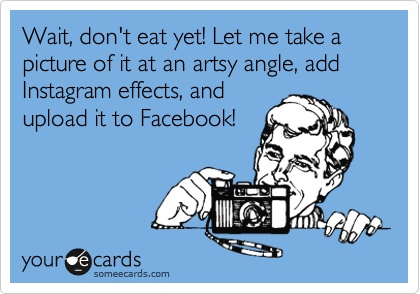Kenapa Polemik Identitas Arsitektur Bisa Terjadi?
Oleh : Rifandi Septiawan Nugroho
Hampir satu dekade Korea Selatan telah berhasil menyebarkan demam “K-Pop” lewat grup musik, film drama, dan reality show ke berbagai negara. Aktor Lee Min Ho mampu membuat para pria rela potong rambut demi terlihat ganteng, bahkan girlband SNSD mampu menggoda para wanita untuk operasi plastik agar terlihat cantik. Begitu pula dengan India, artis Bollywood yang sejak dulu menari di film dramanya, kini diimpor langsung ke acara musik lokal, sambil membagikan hadiah bagi mereka yang mau ikut berjoget di atas panggung. Pada sebagian orang dengan kelas sosial tertentu, mengikuti gayanya adalah kebahagiaan. Gejala yang bisa dibaca sebagai proses penyebaran identitas dalam bentuk yang baru.
Dalam era globalisasi hari ini, memanfaatkan media informasi yang telah menjadi konsumsi utama manusia di planet bumi adalah hal yang kelewat mudah. Saking mudahnya, pertikaian dan persatuan atas dasar identitas bisa bergantian dalam waktu yang sangat cepat. Hari ini bertengkar di media sosial lantaran tim sepak bola idolanya dilecehkan, besoknya berjoget bersama di depan panggung sebagai sesama fans setia. Lantas mengapa berbicara tentang identitas dalam arsitektur di Indonesia begitu membingungkan? Bagaimana manfaat yang sebenarnya telah diberikan olehnya?
Pada 27 Juni 2015 lalu di OMAH Library diadakan diskusi tentang identitas dalam arsitektur di Indonesia dengan mengundang M. Nanda Widyarta, seorang dosen mata kuliah sejarah dan seni di Universitas Indonesia dan Universitas Tarumanegara Jakarta. Paparannya diawali dengan jawaban sederhana dari pertanyaan apa itu identitas. Maknanya terbagi menjadi dua hal. Sebagai penanda yang menempel pada individu atau sebuah kelompok. Mereka berusaha menunjukan fakta “ini adalah saya, bukan dia” dan “ini adalah kami, bukan mereka”. Keduanya berfungsi sebagai penunjuk, penanda, atau pembeda yang memperlihatkan keberadaan.
Dalam diskursus sejarah arsitektur di Indonesia, berulang kali identitas menjadi topik yang hangat untuk dibahas. Pada periode 1920an dan 1980an, identitas pernah menjadi polemik yang muncul ke permukaan. Bahkan hingga hari ini, dimana era globalisasi telah membentuk keberagaman pola pikir tentang arsitektur, isu identitas sering tiba-tiba menjadi sebuah permasalahan yang dianggap penting. Sayangnya, cara menghadapi permasalahan ini seakan-akan pada orientasi yang sama.
Polemik Identitas Dunia
Kesadaran tentang identitas sebenarnya telah terjadi jauh sebelum masehi. Tradisi menandai teritori, membuatan guratan di dinding goa, dan menggambar simbol telah digunakan sebagai penanda seseorang atau kelompok untuk menyampaikan pesan tentang keberadaan mereka. Kemudian kesadaran ini terus berkembang hingga pada satu saat muncul pergolakan di era renaisans sekitar abad ke-14 hingga abad ke-17, berawal dari Italia dan menyebar ke seluruh dataran Eropa. Konon gaya arsitektur dan seni renaisans yang ideal adalah gaya klasik Yunani, atau apa yang mereka sebut antica e buona maiera moderna – gaya modern yang bagus dan kuno.[1] Renaissance memilih jalan romantis dan nostalgia untuk kembali pada keindahan masa lampau.
Pada periode abad ke-18 hingga 20an, modernisme menciptakan mesin-mesin industri yang mendorong munculnya persaingan antar bangsa dalam menunjukan kekuatan. Pembicaraan identitas berkembang sebagai wujud rasa nasionalisme. Pak Nanda memberi contoh karya seni yang dihasilkan oleh seorang pelukis Norwegia Hans Gude. Sebagai seorang profesor termuda di Academy of Art in Dusseldorf , ia dikenal dengan lukisan pemandangan lansekap yang kebanyakan menggambarkan keindahan alam Norwegia. Karya-karyanya muncul pada saat Norwegia menjadi negara yang merdeka dari negara persemakmuran Inggris. Semangat nasionalisme membuatnya berkarya dengan mengangkat keindahan yang dimiliki bangsanya, mengisyaratkan pesan bahwa Norwegia adalah tempat terbaik untuk hidup.
Di negara Hindia Belanda Mccalaine Pont melakukan hal yang hampir sama. Sebagai orang yang tidak suka pada kolonialisme di Indonesia, kemampuan lokal dan arsitektur tradisional yang telah ada dianggap sebagai potensi dalam menghasilkan karya-karya arsitektur. Ia melakukan rekonstruksi situs majapahit di Trowulan, merancang gereja Pohsarang di Kediri dengan inspirasi atap tajuk, dan aula barat ITB dengan inspirasi rumah adat Batak Karo. Seperti Hans Gude, Pont menjadikan eksotisme yang melekat pada subjek sebagai pendekatan dalam berkarya.
Pada abad ke-21, muncul gerakan post-modernisme yang resah akan tawaran universal dari gerakan modernisme sebelumnya. Gerakan baru yang melawan keseragaman dengan mengembalikan identitas sebagai jati diri atau sekedar pembeda sebuah karya dari karya lainnya. Ada yang beranggapan perlawanan dapat dilakukan dengan kembali pada identitas lokal, ada juga yang berbuat semaunya untuk terlihat beda. Proses ini mendorong lahirnya pemikiran konsep seni yang baru. Seperti yang dilakukan oleh Zaha Hadid dalam usaha untuk menunjukan bahwa “ini saya, bukan dia”. Publik pun dapat mengenal dengan mudah karya-karya yang dihasilkannya.
Identitas Arsitektur Indonesia
Setidaknya ada tiga kali perdebatan tentang identitas arsitektur di Indonesia yang menurut Pak Nanda hadir dengan latar belakang yang berbed-beda. Pertama, perdebatan ini muncul di era kolonial. Pada era ini, para arsitek kolonial berusaha membangun istilah “arsitektur Hindia” dalam beberapa pendekatan. Mulai dari usaha menghadirkan arsitektur Belanda di tanah Hindia demi menunjukan karakter kekuasaan, melakukan adaptasi terhadap iklim untuk memaksimalkan performa fungsi bangunan, dan kembali mengangkat akar arsitektur tradisional dan kemampuan lokal untuk mendapatkan sintesis rupa arsitektur yang baru. Ketiganya tetap tidak terlepas dari pandangan yang menjadikan Indonesia sebagai subjek yang pasif, seperti kelinci percobaan.
Kedua, di era pasca kemerdekaan situasi politik negara Indonesia berada di posisi yang belum stabil. Dengan beragam suku dan budaya yang dimiliki Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap perpecahan. Lantas presiden Soekarno membangun visi pembentukan identitas Indonesia yang baru sebagai pemersatu bangsa. Ia tidak merujuk pada satu suku dan budaya tertentu, melainkan sebagai angan-angan wajah baru bangsa Indonesia, yang modern dan tidak kuno. Soekarno ingin menunjukan kepada dunia tentang kekuatan ekonomi negaranya melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran di awal kemerdekaan.
Tantangan ini akhirnya mendorong kongres IAI mulai tahun 1970 hingga 1980-an untuk merumuskan ulang apa sebenarnya identitas arsitektur Indonesia. Friedrich Silaban memasukan konstanta fungsi dan waktu terkait kebutuhan arsitektur. Baginya arsitektur harus mampu menjawab kebutuhan lokal pada saat ia berada, bukan lagi sekedar menunjukan bentuk simbolik dari masa lalu yang tidak fungsional. Adi Moersid bersama Atelier 6 kembali mencoba mensintesis ulang atap rumah Jawa dan diterapkan pada masjid Said Naum, namun dengan bentuk yang masih beroperasi sebagai sirkulasi udara. Gunawan Tjahjono hampir sama, arsitektur atap Indonesia diterapkan sebagai teritisan atap di tiap lantai bangunan gedung rektorat Universitas Indonesia. Namun di akhir perdebatan panjang antara mengutamakan rupa atau fungsi ini para arsitek kembali terhenti di jalan buntu. Arsitektur bergerak terbatas pada dua arus, mengikuti arus global (international style) atau memasukan unsur lokal. Keduanya terjebak pada imaji estetika visual.
Ketiga, setelah tahun 1980-an perdebatan dilanjutkan kembali. Pemikiran tentang arsitektur modern di dunia juga telah digantikan oleh arsitektur posmodern. Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia (LSAI) hadir dengan konsep identitas mereka, yakni “arsitektur nusantara”, sebuah pemahaman yang menggali kembali akar perkembangan arsitektur di Indonesia sebelum diganggu oleh kolonialisme. Profesor Josef Prijotomo dengan tegas menyebutkan bahwa nusantara lebih jelas, memiliki relasi budaya dengan negara-negara lain di Asia Tenggara di luar Indonesia. Gaya arsitektur nusantara juga mengakar pada budaya masyarakat tanah nusantara pada saat sebelum era modern. Dengan memahami dan mendalami kembali arsitektur nusantara, arsitektur yang berjati diri dapat lahir melalui rupa dan jiwanya. Lantas pertanyaan yang selalu muncul kemudian adalah bagaimana wujud nyata dari arsitektur nusantara yang di hari ini, yang mampu menjawab kemajuan zaman dengan segala konsekuensinya.
Perdebatan ini menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa arsitektur di Indonesia. Kegalauan yang bisanya muncul adalah pertanyaan dari mana sebenarnya harus memulai rancangan yang membawa isu identitas arsitektur di Indonesia. Hasilnya tak jarang bangunan gedung bertingkat dipasangkan langsung dengan atap joglo di bagian kepalanya. Seringkali berakhir pada jebakan estetika visual yang lagi-lagi menjadikan arsitektur Indonesia sebagai subjek yang pasif.
Identitas Sekarang? Perlukah?
Sedikit kembali pada sifat dari identitas yang menjadi alat untuk menunjukan ke-aku-an. Munculnya ke-aku-an ini bisa terjadi melalui keinginan untuk mengaku atau diakui. Mengaku mengisyaratkan sifat rela, mau, dan dengan senang hati karena adanya dorongan dari dalam diri. Sedangkan diakui membutuhkan sebuah usaha agar orang lain terdorong melakukannya.
Dalam rangkuman sejarah polemik identitas dunia, ketika ke-aku-an ia dibawa ke lingkup yang lebih luas dari sekedar individu atau bagian kelompok kecil, selalu mengandung konsekuensi politis. Identitas bisa dijadikan alat doktrin akan sebuah fanatisme ideologi, kekuasaan, bahkan komoditas ekonomi dengan tujuan yang berbeda di setiap zaman. Seperti yang diungkapkan Rem Koolhas dalam sebuah sesi wawancara dengan Hans Ulrich Obrist, “Speak of a cultural project today is too limited, and that is partly because culture has become the part of the market economy. Perhaps the only domain that is not entirely absorbed by the market is the political domain itself.”[2] Pernyataan tersebut menunjukan rumitnya mencari kejernihan dari sebuah identitas yang berakar dari budaya masyarakat hari ini yang senantiasa menilai sesuatu sebagai nilai tukar.
Di tengah kerumitan akan pencarian tersebut anggap saja identitas menjadi sebuah permainan yang menyenangkan yang barangkali bermanfaat untuk menyelamatkan Indonesia di tengah arus pasar global. Dengan begitu dibutuhkan konsepsi yang segar dan justifikasi yang merdeka, benar, dan mendalam. Ketimbang meratapi masa lalu arsitektur Indonesia dan menanyakan kembali hal yang sama, lebih baik menghadirkan permainan fiksi baru tentang identitas. Masih banyak fenomena yang baru saja muncul dan memiliki banyak potensi, baik dari segi kehidupan desa maupun kota. Interdisiplin dan kerja komunitas menjadi sebuah kunci taktis yang bisa ditempuh.
Para arsitek Jepang telah berusaha mengeluarkan pernyataan-pernyataan tentang arsitektur mereka hari ini adalah arsitektur yang “Jepang banget”, meskipun bentuk rupanya tidak terasa sama sekali mengadopsi arsitektur Jepang di masa lampau. Menyebarnya paham tersebut belakangan ini hingga membuat arsitek Zaha Hadid kecewa. Seorang arsitek Jepang, Arata Isozaki menyatakan jika desain Zaha Hadid untuk stadion olimpiade 2020 dibangun, Jepang akan terbebani oleh gajah putih raksasa. Berpotensi menjadi aib bagi generasi muda Jepang berikutnya.[3] Selang beberapa lama setelah pasang surut perdebatan itu proyeknya dihentikan begitu saja oleh pemerintah setempat dengan alasan anggaran yang dikeluarkan terlalu besar. Alhasil, Hadid tidak berhasil masuk ke dalam pasar ekonomi Jepang untuk sebuah acara bergengsi dunia. Di sinilah identitas telah memberi contoh peranannya sebagai penangkal rasa terusik.
Arsitek Jepang tidak berjalan sendirian, mereka didukung oleh infrastruktur dari disiplin ilmu lain yang mau bekerja sama. Konsepsi dan rumusan pemikiran para arsitek didukung oleh media yang menguasai pasar dunia seperti A+U dan GA yang dikurasi dengan ketat. Dukungan lain bagi para arsitek diberikan melalui fasilitas cultural exchange seperti Bunkacho Fellowship Award, Asian Cultural Council, dan Japanese Government Overseas Program for Artists. Bahkan bermitra dengan pemerintah berjalan dengan sangat baik seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Kunamoto dengan arsitek Sou Fujimoto mengangkat brandingnya Kunamoto Artpolis. Berbagai penghargaan dan pameran telah menjadi agenda rutin mereka, dengan berkolaborasi dengan pelaku usaha lokal.
Saya tidak menyarankan untuk meniru mentah-mentah apa yang dilakukan oleh Jepang. Di Indonesia sendiri, kesadaran akan kerja kolektif sebenarnya juga sudah mulai bertebaran. Beberapa media alternatif mulai bersuara, kegiatan riset alternatif bergerak, dan kegiatan partisipatoris dengan menggandeng komunitas juga menarik perhatian para mahasiswa. Memunculkan rasa untuk memiliki jauh lebih penting sebelum kita mempertanyakan apa identitas kita.
Pada akhirnya kita perlu bersadar diri, bahwa arsitek Indonesia tidak menjalani hidup sendirian. Baik mengaku-ngaku atau disuruh mengaku, identitas sejati tidak muncul dengan paksaan. Dalam kondisi yang ideal, identitas tidak dinilai milik sebagian kalangan dan pastinya menyebar dengan sendirinya menjadi satu dengan keseharian masyarakat, ia telah mendapatkan apresiasi di tempat yang tepat., Membangun identitas melalui kerja kolektif mungkin akan lebih bermakna ketimbang bentuk simbolik tidak fungsional yang hanya menjadi penanada keangkuhan dan kesombongan mereka yang berkuasa, seperti yang sudah-sudah.
[1] Sardar and Curry, 1995
[2] Hans Ulrich Obrist, 2013
[3] Baca http://www.dezeen.com/2014/11/10/zaha-hadid-tokyo-stadium-olympic-disgrace-arata-isozaki/